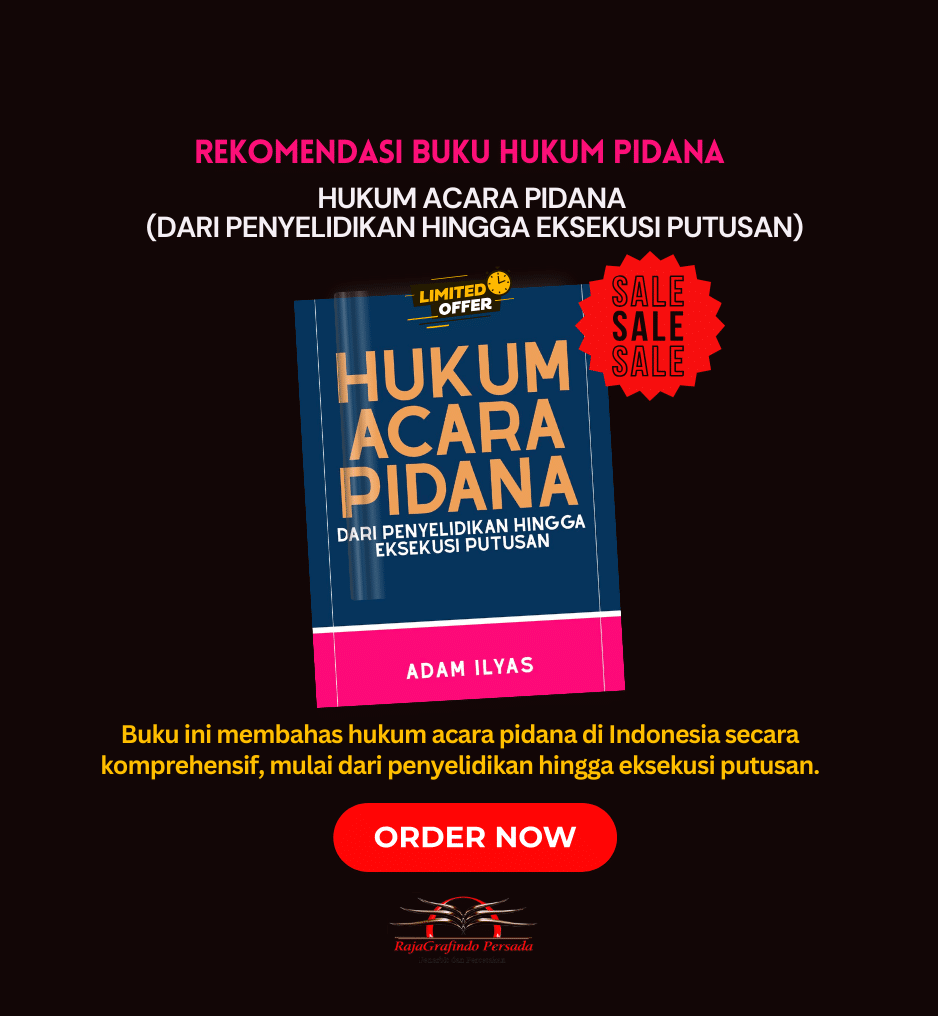Literasi Hukum – Artikel ini mengulas dan menyorot bagaimana kebijakan pemerintah yang melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria.
Pendahuluan
Semangat reforma agararia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah adanya hukum atas tanah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria sendiri merupakan program penataan kembali kepemilikan lahan untuk mewujudkan keadilan atas penguasaan lahan. Penguasaan tahan diorientasikan agar membawa kesejahteraan sosial di samping kesejahteraan individu. Kesejahteraan petani sebagai aktor sentral bagi ketahanan dan kedaulatan pangan juga mendapatkan perhatian lebih karena negara sangat bergantung kepada para petani dalam sektor ini. Tanpa hadirnya petani, maka negara akan menghadapi kesulitan dalam menangani problematika pangan dalam negeri yang dapat berimbas pada aspek lain.
Oleh karena urgensi tata kelola tanah tersebut, negara sebagai pemegang hak prerogatif mengatur hal tersebut dalam kebijakan pemerintahan. UU Nomor 5 Tahun 1960 atau yang biasa disebut UU Pokok Agraria (UUPA) sudah mengamanatkan pengelolaan tanah yang populis agar pengelolaan tanah tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Amanat UU tersebut diturunkan dalam berbagai peraturan dan kebijakan di bawahnya sehingga diharapkan reforma agaria tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Namun dalam dinamikanya, program reforma agraria tersebut sering melenceng dari tujuan pada tahap implementasinya. Pemerintah sebagai otoritas resmi justru sering kali meregulasikan hal-hal yang menyimpang tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, pemerintah abai dan tutup mata terhadap sengketa yang melibatkan reforma agraria ini. Contohnya adalah kejadian yang menimpa para petani di Kabupaten Cianjur tepatnya di Desa Rawabelut dan Desa Batulawang. Kejadian tersebut menjadi salah satu indikasi dari ketidakseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan program reforma agraria tersebut.
Pembahasan
Kasus sengketa agraria yang terjadi di sebuah desa di Kabupaten Cianjur, yaitu Desa Batulawang merupakan sengketa mengenai status tanah yang dikelola menjadi lahan pertanian. Sengketa agraria ini terjadi antara para warga desa tersebut dengan Bank Tanah dan juga melibatkan PT Maskapai Perkebunan Moelya (MPM). Kasus yang terjadi di Batulawang ini bermula ketika pada tahun 1989 PT MPM menjanjikan hak miliki atas bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT MPM seluas 93 ha. Masing-masing warga mendapatkan tanah sekitar 2.500 m2 dan membayar cicilan Rp 20.500.000,00 selama 5 (lima) tahun. Tanah tersebut pada mulanya digunakan untuk peternakan ayam namun gagal di tahun pertama sehingga para warga kembali melanjutkan profesi mereka sebagai petani.
Menjelang akhir Desember 2022, para warga mengusulkan agar lahan seluas 93 ha bekas HGU PT MPM tersebut menjadi lokasi prioritas reforma agraria atau LPRA. Lahan seluas 93 ha tersebut berhasil diregistrasi sebagai objek LPRA demi percepatan reforma agraria. Hal ini sejalan dengan program pemerintah mengenai reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan adanya percepatan reforma agraria tersebut, para warga dapat segera mendapatkan hak milik atas tanah bekas HGU seluas 93 ha tersebut.
Namun dalam realitanya, kepemilikan atas tanah 93 ha tersebut terhambat karena ternyata tanah tersebut telah beralih ke tangan Bank Tanah pada 2023. Menanggapi hal tersebut, Bank Tanah merelokasi LPRA tersebut namun lahan yang direlokasikan sangat tidak ideal untuk dihuni dan dikelola oleh para warga. Para warga kemudian menuntut hak kepemilikan mereka yang direlokasikan dengan tidak ideal tersebut kepada Bank Tanah.
Bank Tanah yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat skema alternatif. Bank Tanah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah meneydiakan lahan pengganti bagi 1927 warga. Para warga tetsebut diberikan hak pakai selama 10 tahun terlebih dahulu. Hak pakai tersebut diberikan secara temporal kepada para warga dan setelah 10 tahun hak pakai tersebut akan menjadi hak milik. Adapun permukiman warga akan dipertahankan terlebih dahulu sementara relokasi lahan garapan warga masih melalui tahap pembahasan.
Pemberian hak pakai sementara dan kemudia diikuti dengan perubahan menjadi hak miliki ini menurut GTRA dilakukan demi melindungi petani itu sendiri. Program redistribusi berkaca pada pengalamann sering diakali dengan cara petani mengalihkan hak miliknya tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN menilai cara ini dapat memberikan perlindungan petani.
Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mengkritisi kebijakan agraria yang diterapkan pemerintah melalu Kementerian ATR/BPN tersebut. KPA menilai tidak adanya jaminan setelah 10 tahun hak pakai tersebut akan menjadi hak milik, hak secara penuh kepada petani. Di samping itu, para warga sejaka Orde Baru (Orba) sudah membangun kampung mereka sendiri dan memiliki tanah sebagai indikasi akan eksitensi mereka. Namun dengan adanya kebijakan ini, mereka harus membuktikan eksistensi mereka lagi selama 10 tahun ke depan dan ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan.
Analisis Kasus
Program reforma agraria sebagai program yang berorientasi pada penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan dan pengusaan tanah memiliki beberapa program implementatifnya. Di antara program implementatif tersebut adalah redistribusi lahan atau pembagian tanah. Tanah yang akan diredistribusikan tersebut adalah tanah yang melebihi batas maksimal kepemilikan, tanah absentee atau tanah yang berlokasi berjauhan dengan domisili pemiliknya, tanah swaparaja, dan tanah negara. Tanah objek reforma agraria atau TORA ini akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan agar terjadi pemerataan tanah.
Program redistribusi ini pada dasarnya adalah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan individu terkhususnya para petani yang berperan penting bagi penyediaan pangan. Tanah yang ditinggalkan pemiliknya, atau berlokasi berjauhan dari domisili pemiliknya, atau melebihi batas diatur sedemikian rupa oleh negara melalui UUPA agar pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara maksimal. Sama halnya dengan relokasi lahan yang menjadi objek sengketa antara masyarakat Desa Batulawang dengan Bank Tanah tersebut.
Dari sudut pandang pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, relokasi lahan tersebut dilakukan agar melindungi masyakarat. Namun sejatinya relokasi lahan tersebut memiliki kejanggalannya tersendiri. Lahan pengganti yang disediakan pemerintah melalui Bank Tanah sangat tidak ideal untuk dihuni dan dikelola sehingga nilai tanah relokasi tersebut jauh di bawah tanah asli mereka. Para warga tidak dapat bertani di lahan pengganti tersebut sehingga tujuan relokasi tersebut hampa. Tidak ada gunanya mengganti tanah yang produktif dengan tanah yang tidak produktif.
Bank Tanah sebagai bank yang diberikan wewenang melaksanakan redistribusi lahan seharusnya memberikan lahan pengganti yang layak. Lahan pertanian yang dijadikan para warga sebagai lahan pertanian tersebut tidak boleh hanya sekadar diganti dengan tanah yang tidak layak atau bahkan hanya sekadar uang pengganti. Ditambah lagi tanah bekas HGU seluas 93 ha tersebut sudah didaftarkan sebagai objek LPRA. Seharusnya tanah tersebut tidak boleh dialihkan karena program redistribusi tanah menghendaki adanya pembagian tanah beserta hak miliknya kepada masyarakat yang membutuhkan.
Inti dari program redistribusi adalah masyarakat memiliki hak milik atas tanah objek reforma agraria atau TORA yang mana sebelumnya mereka bahkan tidak memiliki hak milik atas tanah. Program redistribusi tidak mengenal adanya pembagian hak pakai karena hak pakai tidak sekuar hak milik. Hak milik sendiri merupakan hak penuh dan hak yang paling tinggi dibandingkan hak lainnya seperti hak pakai dan HGU. Dengan hak milik, para warga dapat mengelola tanah mereka sendiri secara penuh seperti memindahtangankan tanah tersebut atau menempatkan hak tanggungan. Sementara hak pakai hanya bersifat temporal dan tidak sekuat hak milik. Oleh karena itu hak milik ini tidak dapat dialihkan menjadi hak pakai walaupun hanya sementara yaitu 10 tahun.
Pemberian hak pakai kepada masyarakat yang pada dasarnya mereka memiliki hak milik merupakan bentuk penyelewengan terhadap semangat reforma agraria. Masyarakat yang semula memiliki kepastian kepemilikan atas tanah akan menemui ketidakpastian hukum karena status tanahnya berubah menjadi hak pakai. Pembatasan waktu 10 tahun tersebut juga sangat potensial untuk diselewengkan. Sebagaimana yang dikatakan KPA, tidak ada jaminan setelah 10 tahun hak pakai tersebut akan berubah menjadi hak milik. Akan sangat mungkin Bank Tanah sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut memindahtangankan kembali tanah tersebut. Jika ini terjadi, maka hak masyarakat atas tanah tersebut akan hilang karena status mereka hanya sebatas pemegang hak pakai.
Kesimpulan
Amanat UUPA yang dicita-citakan menciptakan sistem hukum yang menata pertanahan secara berkeadilan seharusnya diimplementasikan oleh pemerintah dalam setiap kebijakan. Pemerintah sebagai otoritas yang berwenang seharusnya berkomitmen dalam melakukan reforma agrarian terutama setelah adanya program percepatan reforma agraria tersebut. Kebijakan pemerintah melalui kementerian, Bank Tanah, dan lembaga terkait seharusnya satu kata dalam menjalankan program ini karena akan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.