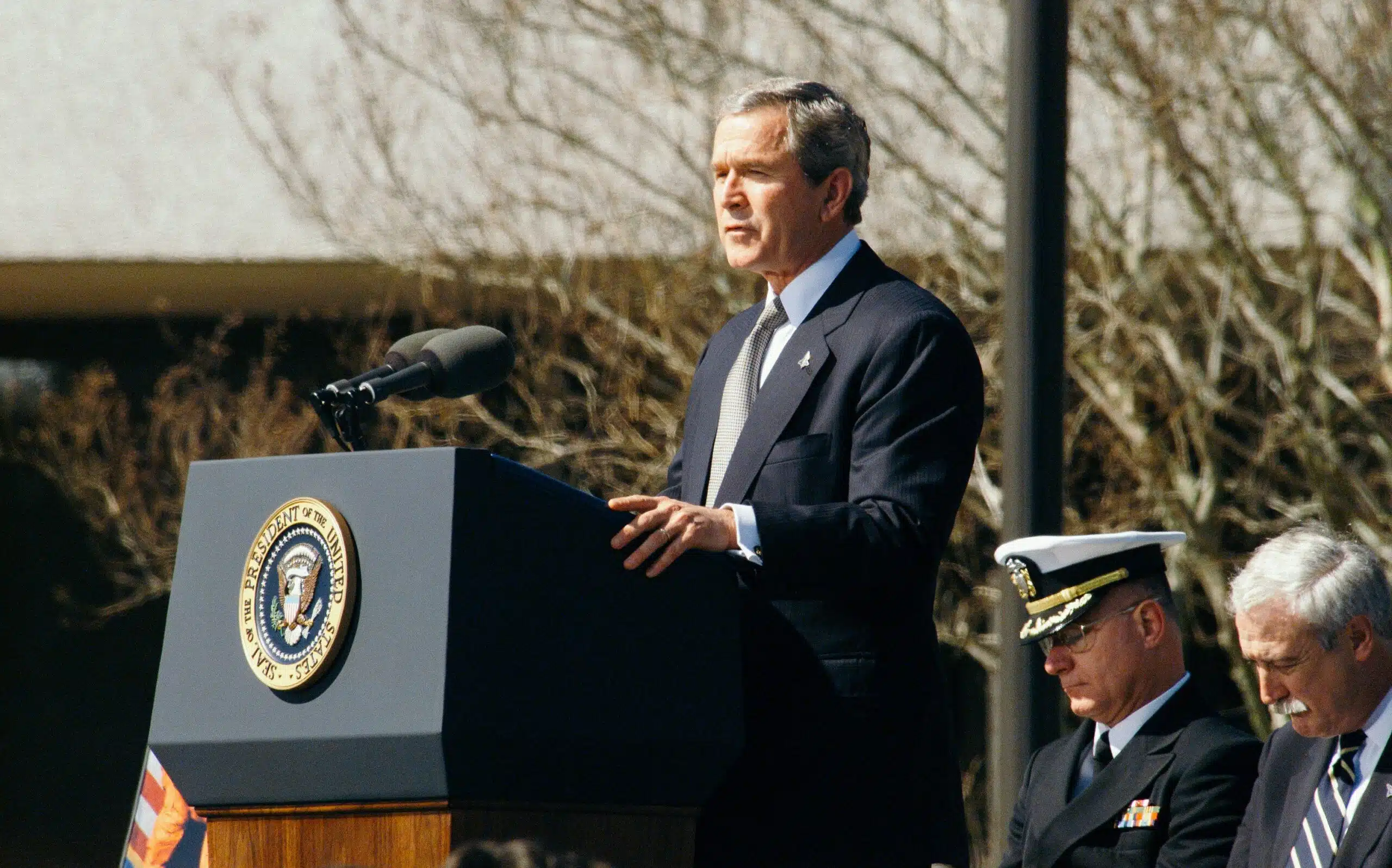Pada kampanye pemilu, presiden yang menjabat dapat ikut serta dalam kampanye dari calon presiden yang akan menggantikannya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (“UU Pemilu”).
Hanya saja, jika presiden ikut serta dalam kampanye pemilu, ada potensi sikap presiden berpihak. Hal ini dapat menguntungkan calon presiden tertentu. Beberapa riwayat pemilu telah membuktikannya.
Di Uruguay, calon presiden Jose Mujica berhasil memenangkan pemilu Uruguay 2009 dengan total suara sebesar 52,4% di putaran kedua setelah didukung oleh presiden petahana Tabare Vazquez. Pada pemilu AS 2016, dukungan presiden Barack Obama membuat calon Presiden Hillary Clinton meraih total suara rakyat sebesar 48,2% dibandingkan lawannya, Donald Trump yang meraih 46,1%.
Setidaknya, keberpihakan presiden dalam kampanye pemilu mendongkrak elektabilitas calon presiden tertentu. Jika pemilu terdiri atas lebih dari 1 calon presiden, sikap presiden yang berpihak tentu merusak kontestasi pemilu yang sedang berlangsung.
UU Pemilu telah mengatur perihal keberpihakan presiden dalam kampanye pemilu. Namun, pengaturan UU Pemilu tetap memiliki celah. Artikel ini membahas celah tersebut.
Sebuah Hak dan Larangan
Mayoritas pendapat menyatakan, sikap presiden yang berpihak dalam kampanye pemilu adalah hak dan larangan.
Dalam konteks hak, sikap presiden berpihak merujuk pada hak asasi miliknya untuk terlibat dalam pemilu. Presiden merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih-dipilih. Ini tidak diatur dalam UU Pemilu, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), tepatnya pada Pasal 43 ayat (1).
Ketika seseorang menentukan pilihan, mereka secara otomatis menentukan keberpihakan. Dengan logika demikian, meskipun UU HAM tidak eksplisit mengatur apakah hak memilih-dipilih sepaket dengan hak memihak, UU HAM tetap dianggap mencakup kedua hak tersebut. Ini adalah argumentasi pendukung hak presiden untuk memihak.
Hanya saja, kesatuan antara hak memilih dan hak memihak tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang berstatus pejabat negara. Alasannya, pejabat negara memiliki “jabatan” yang membatasi hak mereka untuk menentukan keberpihakan, termasuk pada calon presiden dalam kampanye pemilu.
Pejabat negara yang memihak calon presiden rentan terlibat dalam konflik kepentingan. Pejabat memiliki kepentingan berdasarkan jabatannya, sedangkan calon presiden memiliki kepentingan untuk memenangkan pemilu. Jika pejabat memihak pada calon presiden tertentu, dikhawatirkan pejabat akan menyalahgunakan jabatannya untuk membuat calon presiden tadi mencapai kepentingannya.
Bentuk penyalahgunaan jabatan itu dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan perangkat negara untuk fasilitas kampanye hingga penerbitan keputusan yang mendiskriminasi peserta pemilu. Secara esensial, penyalahgunaan itu melanggar hukum dan hanya menguntungkan peserta pemilu yang didukung.
Jika dikaitkan dengan kedudukan presiden sebagai pejabat negara, alasan-alasan di atas menjadi kian relevan. Presiden mengemban jabatan dengan level kekuasaan yang besar. Dengan kekuasaan itu, ia bisa saja mengerahkan segala sumber daya demi mengatur kemenangan calon presiden yang ia dukung.
Untuk itulah, setidaknya di Indonesia, presiden dilarang untuk berpihak dalam kampanye pemilu. Ini diatur melalui Pasal 283 UU Pemilu. Diatur bahwa bentuk keberpihakan apapun yang dilarang, termasuk pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang, dan berlaku sebelum, selama, dan sesudah kampanye.
Celah Aturan bagi Presiden Berpihak
Dalam kampanye pemilu, Pasal 283 UU Pemilu memang mengatur larangan bagi presiden untuk menunjukkan keberpihakan. Namun, presiden memiliki hak untuk berkampanye dengan dasar keberadaan hak untuk memilih-dipilih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM.
Hak presiden untuk berkampanye diatur dalam Pasal 299 UU Pemilu. Secara normatif, pasal ini memang tidak mengurangi ketentuan Pasal 283 UU Pemilu. Alhasil, presiden tetap dapat melakukan kampanye tanpa menunjukkan sikap berpihak terhadap peserta pemilu tertentu.
Hanya saja, pada uraian sebelumnya, telah disinggung bahwa hak memilih-dipilih berlaku bersamaan dengan hak untuk memihak. Untuk itu, meskipun presiden mengklaim bahwa ia melakukan kampanye netral, potensi kecenderungan dirinya untuk memihak pada calon presiden tertentu akan tetap ada.
Dengan demikian, alih-alih menjadi norma pembeda antara hak memihak dan hak untuk berkampanye, Pasal 299 UU Pemilu justru menjadi norma yang berpotensi menjangkau keduanya secara bersamaan. Pasal ini membuka celah bagi presiden untuk menentukan keberpihakan dengan kedok menjalankan haknya sebagai warga negara untuk memilih-dipilih.
Potensi celah itu makin kuat dengan mempertimbangkan 2 hal. Pertama, tidak ada sanksi bagi presiden yang melanggar ketentuan Pasal 283 UU Pemilu. Ini berbeda dengan pejabat negara ASN atau TNI-POLRI; mereka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan tingkat institusional.
Kedua, belum ada preseden di Indonesia mengenai penjatuhan hukuman bagi presiden yang memihak dalam kampanye pemilu. Ini mempersulit upaya untuk mengajukan akuntabilitas terhadap presiden yang terbukti telah berpihak, terutama dalam menentukan indikator dan jangkauan keberpihakannya.