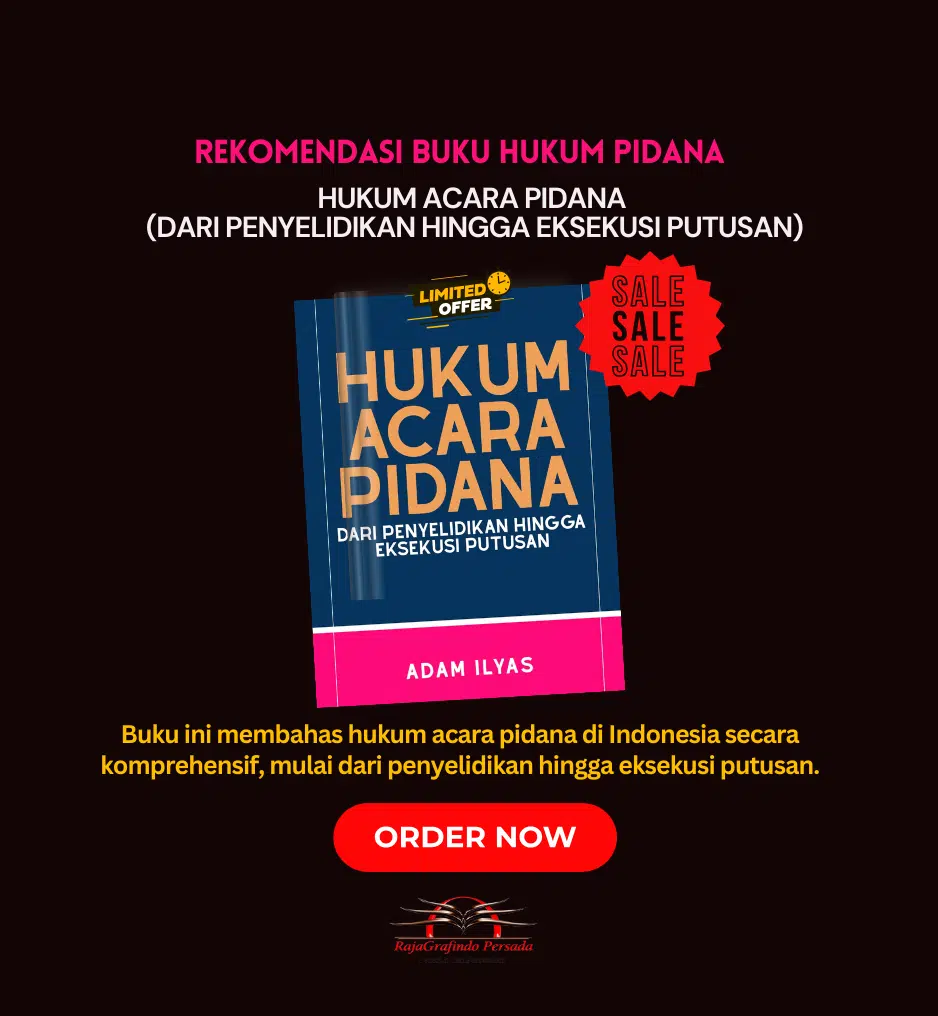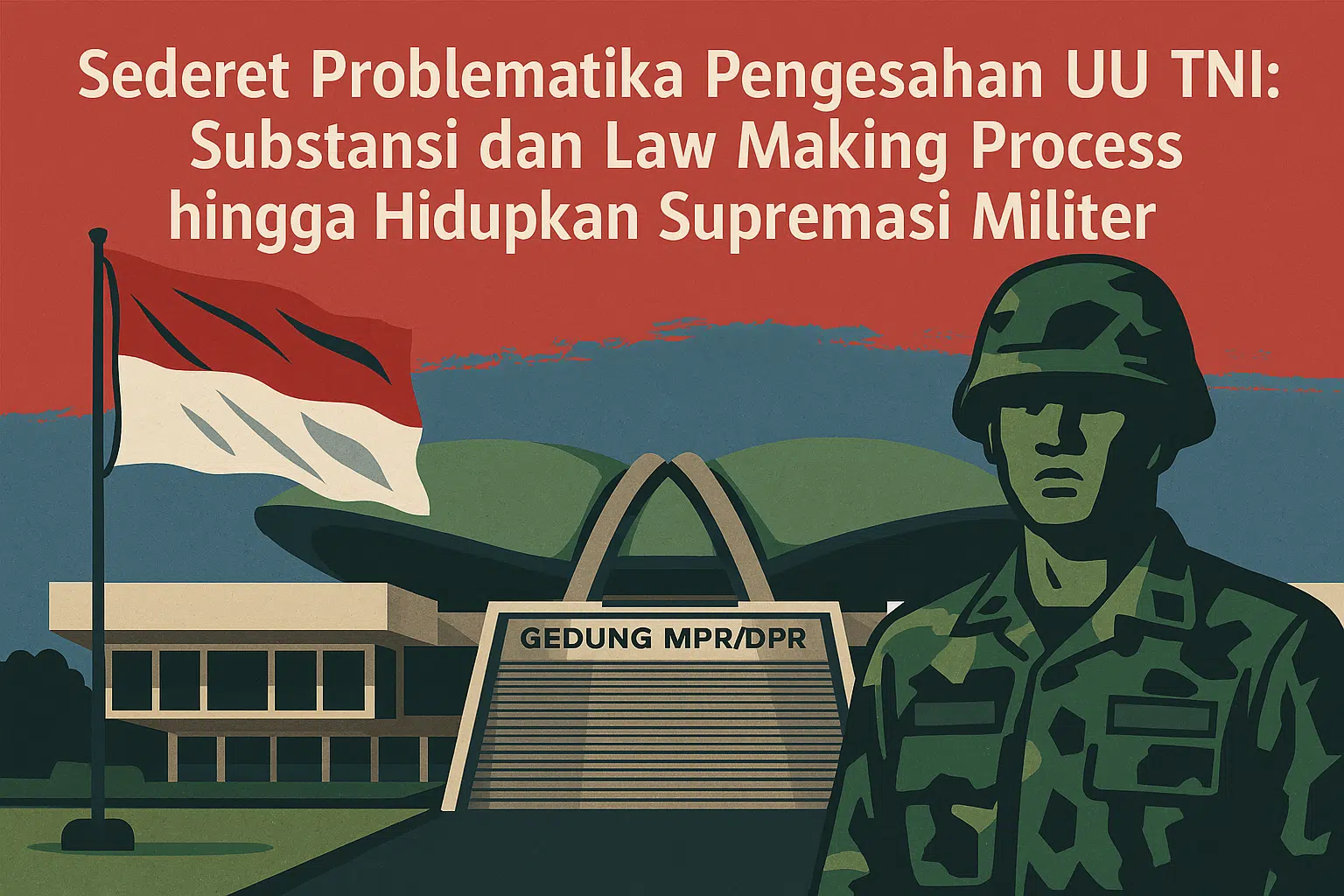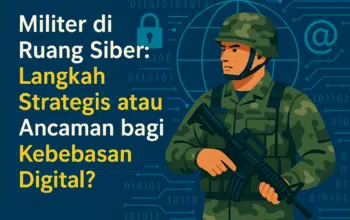Literasi Hukum – Kamis, 20 Maret 2025 di tengah pusaran penolakan, publik dikejutkan dengan pengesahan revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Alih-alih membentuk produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah justru melakukan prosesi perubahan Undang-Undang atas UU TNI yang dilakukan secara serampangan. Perubahan terhadap 3 Pasal, yakni pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53 dikebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dalam ruang tertutup. Sangat berbanding terbalik dengan negara yang menjunjung tinggi hukum diatas segalanya. Perubahan ketiga pasal tersebut disinyalir mereduksi supremasi sipil, dan memperkuat supremasi militer.
Mengenal Supremasi Sipil Dan Supremasi Militer
Secara sederhana, supremasi sipil merujuk pada prinsip bahwa otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan negara berada di tangan pemerintahan sipil, bukan di tangan militer. Prinsip ini menegaskan bahwa militer harus tunduk pada kendali dan pengawasan oleh otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, seperti presiden, parlemen, atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Supremasi sipil adalah kunci dalam sistem demokrasi, agar memastikan bahwa kebijakan publik dapat merepresentasikan keinginan rakyat.
Berbeda dengan supremasi militer, yang merujuk pada unsur militer yang memiliki dominasi keputusan politik dan pemerintahan suatu negara. Kondisi ini memungkinkan militer dapat mengontrol atau bahkan menggantikan otoritas sipil, baik secara langsung (kudeta, misalnya) maupun secara tidak langsung melalui tekanan atau intervensi dalam kebijakan. Supremasi militer sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi karena mereduksi peran lembaga sipil yang dipilih oleh rakyat.
Supremasi militer sering terjadi di negara yang cenderung mengalami ketidakstabilan politik, lemahnya institusi sipil, atau tradisi demokrasi yang belum matang. Indonesia pernah mencatatkan sejarah supremasi militer pada masa orde baru dengan ciri khas dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang pada masa itu mendominasi pada keputusan politik di Indonesia.
Catatan Historis Dwifungsi Abri Dan Instabilitas Sosial Dan Politik
Kebijakan dwifungsi ABRI ini berlaku pada masa rezim pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 Tahun. Dwifungsi ABRI diberlakukan oleh Soeharto pada tahun 1982 melalui UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Pasca berlakunya UU tersebut, ABRI berhasil melakukan dominasi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif pada pemerintahan Orde Baru.
Secara sederhana dwifungsi ABRI merupakan konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentara dalam tatanan kehidupan bernegara. Dengan adanya dwifungsi ABRI maka dilain tantara menjalankan perannya sebagai alat pertahanan negara, juga dapat sekaligus menjalankan tugas sebagai pengatur negara.
Faktanya, dominasi militer dalam ranah sipil menuai berbagai kecaman dari masyarakat. Terutama terkait dengan praktik otoritarianisme dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pada saat itu, mulai dari bupati, wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet rezim Soeharto didominasi oleh pihak militer. Akibatnya keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik yang semakin mendalam menyebabkan militer bergeser menjadi alat perlindungan rezim atas pembenaran atas kebijakan pemerintah.
Singkatnya, setelah reformasi 1998, dwifungsi ABRI mulai dihapuskan melalui Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI yang muncul akibat tuntutan reformasi yang menjunjung tinggi reposisi dan restrukturisasi demi mewujudkan demokrasi yang ideal. Adanya TAP MPR tersebut menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dalam arti eksternal, sedangkan POLRI ditempatkan sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dalam arti internal. TAP MPR tersebut juga menandakan bahwa Indonesia memasuki babak baru dimana militer tidak lagi memiliki peran ganda dalam politik, dan supremasi sipil semakin diperkuat.
Prosedur Pembuatan Perundang-Undangan pada Revisi UU TNI Dinilai Serampangan
Perlu diketahui bahwa RUU TNI masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pasca terbitnya Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama menilai secara universal revisi UU TNI telah keluar dari semangat reformasi, ketentuan konstitusi, dan prosedur legislasi. Terdapat beberapa hal yang dapat dinilai bahwa prosedur revisi UU TNI dinilai serampangan antara lain:
Pertama, RUU TNI tidak sah sebagai RUU Prioritas dalam Prolegnas 2025. Hal tersebut lantaran masuknya RUU TNI sebagai RUU Prolegnas Prioritas tidak melalui pertimbangan Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR). Pertimbangan tersebut penting lantaran mencakup pembahasan mengenai dapat atau tidaknya suatu RUU masuk dalam prolegnas perubahan sebagaimana Pasal 67 ayat (3) tatib DPR. Sehingga seolah-olah RUU TNI yang baru ini disahkan merupakan produk hukum selundupan yang merupakan orderan dari segelintir orang.
Kedua, cepatnya respon DPR dan menyetujui usulan presiden sebagaimana dalam Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 hanya dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Persetujuan yang dinilai cepat ini kontras dengan Nasib RUU lain yang lebih pro-rakyat, seperti RUU Perampasan Aset yang telah mangkrak bertahun-tahun. Sehingga RUU TNI tidak sah sebagai RUU Prioritas karena melangkahi tahap penyusunan dan prosedur pembentukan UU. Dalam hal ini Rizky Argama berpendapat bahwa jika terdapat kelalaian pelaksanaan tugas tersebut, seharusnya menjadi tanggung jawab Baleg DPR yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ketiga, dalam proses pembahasannya, RUU TNI disinyalir tidak transparan, tertutupnya pembahasan RUU TNI menyebabkan mampetnya ruang partisipasi publik. Draft RUU TNI tidak pernah disebarluaskan secara resmi oleh DPR. Akibatnya, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna (meaningfull participation). Hal tersebut diperburuk oleh komunikasi DPR yang sempat menyudutkan masyarakat yang kritis dengan menyebutkan draft yang digunakan tidak sama dengan draft yang sedang dibahas. Tidak hanya itu, pembahasan RUU TNI dilaksanakan di dalam hotel dengan tingkat keamanan tinggi, sehingga ruang publik untuk mengetahui pembahasan RUU ini semakin tertutup.
Dengan tingkat penolakan yang tinggi dari masyarakat, diperparah dengan misprosedural yang fatal. DPR dalam hal ini bersikukuh untuk mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang dengan perubahan pasal yang menuai kontroversial hingga disinyalir menghitupkan kembali dwifungsi ABRI yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.
Pengesahan RUU TNI: Potensi Hidupkan Dwifungsi ABRI dan Mereduksi Supremasi Sipil ?
Ditengah gejolak penolakan dari berbagai pihak dari semua kalangan. Justru DPR dalam Rapat paripurna akhirnya mencapai kesepakatan pada hari Kamis 20 Maret 2025 dan menjadikan RUU TNI untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU TNI menjadi UU membawa beberapa implikasi yang cukup luas, baik dari aspek pemerintahan, keamanan, maupun keseimbangan antara sipil dan militer yang cenderung akan mengaktifkan kembali dwifungsi ABRI. Adapun perubahan tersebut antara lain:
Pertama, Perubahan UU TNI berpotensi mencederai supremasi sipil yang telah bangun oleh konstitusi UUD 1945. Perubahan Pasal 47 memberikan perluasan peran TNI di Sektor Sipil dengan bertambahnya jumlah kewenangan bagi prajurit aktif militer untuk menduduki jabatan di beberapa Kementerian yang awalnya 10 lembaga negara menjadi 14 lembaga negara. Perubahan ini jelas bertentangan dan menggerogoti supremasi sipil negara demokrasi, yakni kedudukan militer di bawah otoritas sipil sebagaimana semangat TAP MPR No. VI/MPR/2000.
Alih-Alih memperkuat koordinasi di bidang keamanan nasional dan tanggap darurat, justru revisi UU TNI menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi ABRI. Hal ini karena tidak adanya frasa pembatasan dalam nomenklatur perubahan UU TNI yang menyebutkan bahwa TNI aktif hanya bisa dapat menduduki jabatan sipil sesuai dengan kompetensinya, yakni di bidang pertahanan dan keamanan. Tidak adanya nomenklatur tersebut seakan-akan TNI dapat menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
Kedua, perubahan UU TNI pada Pasal 7 disinyalir mereduksi Supremasi Sipil dengan menambahkan kewenangan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang merambah kepada penanggulangan ancaman siber, penyelamatan WNI di luar negeri, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, prekursor, dan zat adiktif. Penambahan kewenangan tersebut menjadi polemik di masyarakat lantaran masuknya TNI dalam ruang siber berpotensi merenggut kebebasan berpendapat, dan berekspresi yang telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Ketiga, perubahan UU TNI pada Pasal 53 yang pada intinya memperpanjang batas usia pensiun TNI. Untuk bintara dan tamtama maksimal pada usia 55 (lima puluh lima) Tahun, perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun, dan khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Perpanjangan batas usia pensiun TNI disinyalir akan menghambat karier TNI, membebani APBN, dan akan memperburuk manajerial terkait pembinaan TNI.
Revisi UU TNI tepatnya pada tiga pasal tersebut berpotensi membuka ruang bagi prajurit aktif menduduki jabatan sipil berarti juga dapat diartikan sebagai mereduksi supremasi sipil yang meresiko menciptakan carut marut dalam dunia percaturan sosial dan politik. Pengesahan Revisi UU TNI pada 20 Maret 2025 berpotensi pengambilan keputusan politik yang cenderung kembali pada sistem komando. Dimana model komunikasi politik di segala aspek didasarkan pada hierarkis (Top to Bottom) bukan pada model demokratis (Bottom to Top) sehingga dalam hal ini dapat mencederai sistem demokrasi yang telah diperjuangan sejak masa reformasi.